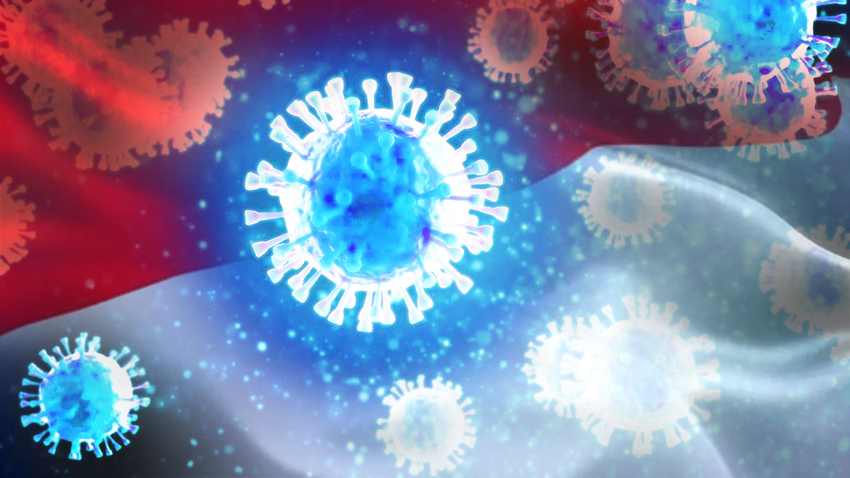
17 Juli 2021

Oleh: Sulistyowati Irianto
Guru Besar Antropologi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Karena kita tidak memiliki tradisi dan rasa kebutuhan untuk memiliki basic research, maka tidak mudah menghadapi pandemi yang mendadak datangnya.
HARI-HARI INI kita tidak hanya bisa bilang Indonesia musim kemarau atau musim hujan, tetapi juga musim kematian.
Setiap orang mengalami hampir setiap hari ada kabar duka, kehilangan orang yang kita kenal, sahabat, kerabat bahkan bisa dua atau tiga kali sehari. Betapa ngeri dan was-was setiap membuka group whatsapp, surat khabar, medsos, suara sirene ambulans di depan rumah, atau toa di mesjid. Semuanya mengabarkan berita duka. Aroma kematian tercium di mana-mana.
Minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu masih bersapa seseorang, hari ini tiba-tiba dia sudah tak terselamatkan. Rasanya seperti ada Dementor di atas genting rumah kita, sehingga jalan penyelamatan memang hanya tinggal di rumah.
Sudah menjadi berita keseharian, kita bukan hanya kesulitan mendapat obat, vitamin dan oksigen; tetapi juga rumah sakit yang penuh, sampai harus diperluas ke berbagai gedung, bangunan dan tenda di pelataran parkir; dan bahkan kesulitan mendapatkan kuburan.
Salah siapa?
Mari kita telisik…
Tidak semua penjelasan yang begitu banyak bisa dikompilasi, tetapi beberapa hal dapat diidentifikasi.
Pertama, orang paling bertanggung jawab dalam bidang kesehatan pernah sangat menyangkal bahwa Covid-19 juga bisa menghantam Indonesia. Responnya mulai bergugurannya terhadap para dokter dan tenaga kesehatan menunjukkan ketiadaan empati.
Kebijakan lanjutan terhadap ‘kosongnya kepemimpinan’ dalam bidang kesehatan, lama diputuskan, sampai ada pejabat baru menggantikan; Sementara angka kematian terus terjadi. Selanjutnya team penanganan Satgas nasional, daerah, bagaimana kerjanya? Keterlambatan pencairan dana dikeluhkan tenaga kesehatan dan penyedia layanan dan fasilitas kesehatan di berbagai daerah.
Salah siapa?
Kedua, ketiadaan perasaan kedaruratan dalam masyarakat sendiri tidak bisa disangkal. Enam juta orang pulang kampung, padahal ada larangan. Ada pembatasan pengguanan moda transportasi publik berupa bus, kereta, dan kendaran umum lain, tetapi semua larangan dapat diterobos melalui segala muslihat. Berangkat sebelum hari ‘H’ pelarangan. Atau naik motor jarak jauh pun jadilah. Jutaan motor di jalan raya, berdekatan, berdempetan. Bisa dibayangkan bagaimana peredaran virus terjadi secara masif dan intensif.
Akibatnya adalah meledaknya angka positif virus harian sejak bulan Juni silam sampai hari ini, mencapai lima puluh tujuh ribu per hari (16 Juli), dan angka kematian seribu lebih! Dan masih ada yang tidak terlacak, tentunya angka sesungguhnya masih lebih dari ini.
Salah siapa?
Ketiga, munculnya penolakan terhadap testing (yang padahal penting sekali) di berbagai tempat seperti di Madura bahkan pedagang pasar di dekat rumah saya; Penolakan terhadap vaksin, sampai penolakan terhadap berbagai kebijakan lockdown darurat (apapun nama kebijakannya), karena disinformasi Covid-19 termasuk hoax dan Covid–idiot (juga yang bawa-bawa agama).
Salah siapa?
Keempat, peristiwa kedua dan ketiga, adalah akibat dari ketidakberhasilan pemerintah berkomunikasi dengan segenap warga masyarakat, membangun literasi tentang pandemi Covid-19 dan bahayanya. Kegagalan pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa ini untuk memerangi Covid-19.
Warga masyarakat tidak paham mengapa tidak boleh berkerumun, harus tinggal di rumah sebanyak mungkin termasuk memindahkan kegiatan ibadah ke rumah masing-masing. Kalau terpaksa keluar, mengapa harus jaga jarak satu meter, harus pakai masker, harus cuci tangan. Bagaimana cara pakai masker mengapa harus rapat — bukan ditaruh di dagu , bagaimana cuci tangan yang bukan asal-asalan.
Memang ada komunikasi, penjelasan tetapi tidak memadai karena tidak bisa menjangkau masyarakat yang beragam secara geografis, pendidikan, kelas sosial dan tidak mampu membuat mereka melek kesehatan dan melek hukum.
Salah siapa?
Kelima, para ilmuwan berbuat apa? Karena kita tidak memiliki tradisi dan rasa kebutuhan untuk memiliki basic research, maka tidak mudah menghadapi pandemi yang mendadak datangnya.
Memang ada para ilmuwan yang bekerja keras dan menghasilkan berbagai temuan (asli orang Indonesia, keren kan?) seperti penemuan plasma convalescent dari survivor untuk didonorkan kepada yang sakit, percobaan pembuatan vaksin yang dilakukan oleh beberapa pusat penelitian seperti Eijkman, Biofarma, dan universitas seperti Airlangga dan Unpad yang konon baru akan jadi akhir tahun ini atau awal tahun depan, penemuan GNose UGM, ventilator UI, dan lain-lain — terlepas dari keandalannya teruji di jurnal seperti the Lancet dan terakreditasi di PubMed, pokoknya sudah dilakukan, dan upaya ini harus dihargai setinggi-tingginya.
Dengan kondisi ‘gedandapan’, dan keterbatasan dana yang — seperti biasanya — tidak mudah turun karena hambatan birokrasi dari KemendikbudRistek dan Kemenkeu, pokoknya upaya itu sudah ada. Ilmuwan Sosial humaniora juga tidak sedikit yang menyumbangkan pemikiran dan rekomendasi dari perspektif ekonomi, sosial-budaya dan psikologi.
Keenam, mengapa tubuh orang Indonesia rentan? Kematian begitu banyak, dibandingkan dengan negara yang angka positifnya lebih banyak atau lebih sedikit tetapi prosentasi kematiannya lebih rendah dari Indonesia. Kompas tanggal 16 dan 17 Juli, hari ini, mengangkat isu kekebalan antibiotik tubuh yang diduga disebabkan mata rantai makanan seperti unggas yang diberi antibiotik tanpa kendali.
Salah siapa?
Ada banyak lagi soal, dan mempertanyakan salah siapa dirasa penting oleh khalayak untuk berbagai alasan. Tetapi dalam situasi bau anyir kematian kolektif seperti ini, mencari ‘salah siapa’ dapat ditunda. Hal yang dibutuhkan adalah ‘just in time theory’ tentang apa yang bisa dibuat.
Pandemi tidak bisa diselesaikan tanpa mengajak masyarakat ikut terlibat. Tak mungkin diserahkan kepada pihak-pihak tertentu saja.
Nanti sesudah pandemi lewat mari kita menyoal lagi, ‘salah siapa’, di mana salahnya, dan bagaimana strateginya menghadapi pandemi berikutnya, yang kemungkinan besarnya virus Corona akan menjadi bagian dari New Normal dan keseharian hidup kita, sama seperti virus Influenza. (*)
Editor: Daniel Kaligis